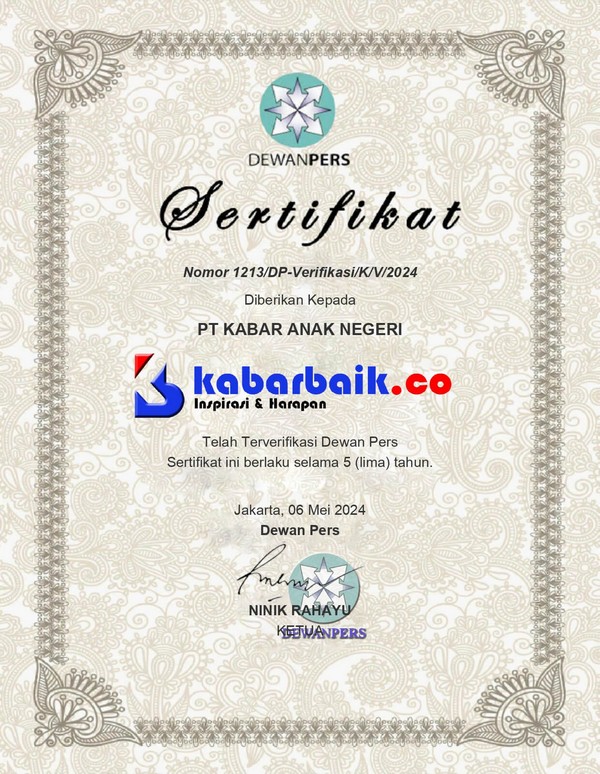OLEH: BOIMIN PhD)*
PEMERINTAH menghentikan impor empat komoditas pangan. Yakni, beras, gula, garam, dan jagung. Kebijakan itu merupakan bentuk konkret mendukung kemandirian pangan nasional. Namun, kebijakan itu perlu didukung dengan kajian mendalam dan perencanaan yang matang dari masing-masing kom0ditas. Sebab, setiap komoditas mempunyai peluang dan tantangannya sendiri. Jangan sampai penghentian impor empat komoditas pangan itu, justru kontraproduktif dengan tujuan awal.
Beras, misalnya. Penghentian impor beras itu baik dengan syarat cadangan beras nasional mencukupi. Penghentian impor beras dengan serta merta, tanpa ada perencanaan dan analisa yang baik, justru akan menyengsarakan rakyat. Harga beras bisa melambung tinggi akibat kelangkaan beras di pasar. Ekonomi nasional bisa terganggu. Sebab, beras adalah makanan pokok rakyat Indonesia.
Solusi sebelum menghentikan impor beras. Pemerintah memiliki cadangan beras yang cukup, telah memiliki kajian yang lengkap terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produksi beras dalam negeri—misalnya faktor iklim dan cuaca dan faktor geopolitik internasional.
Pemerintah memiliki prakiraan (forecast) cuaca/iklim sampai lima tahun ke depan, dan menyiapkan langkah antisipatifnya dari sekarang. Pemerintah juga perlu menyiapkan rencana darurat (contingency plan) seandainya terjadi kemungkinan terburuk. Misalnya, terjadi gagal panen di dalam negeri, dan di saat bersamaan terjadi perang yang mengakibatkkan pasokan beras dari luar negeri terganggu.
Target bisa menghentikan impor beras tahun 2025 itu sangat menantang, meskipun produksi padi kita normal. Indonesia bisa mempertahankan kondisi saat ini dan bisa menurunkan impor beras sedikit demi sedikit, secara bertahap saja, itu sudah bagus.
Hal itu didasarkan fakta bahwa Indonesia masih impor beras, bahkan di tahun 2023 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 3,06 juta ton. Itu terbesar dalam lima tahun terkahir. Terlebih, tidak mudah memperbaiki tata niaga beras kita. Apalagi jika ada kepentingan lain yang mendompleng impor beras. Waktu satu tahun bisa jadi terlalu singkat.
Contoh lainnya, gula. Ada empat persoalan pokok yang menyebabkan kita masih impor gula. Pertama, produktivitas dan rendemen tanaman tebu kita rendah—7,61 persen di tahun 2021. Kedua, kapasitas mesin penggiling tebu kurang besar dan jumlah pabrik gula kita masih kurang dan usianya tua, banyak yang peninggalan Belanda—59 pabrik gula di tahunn 2023. Ketiga, luas lahan tebu masih kurang—504,8 ribu hektar di tahun 2023. Keempat, tata niaga gula yang belum baik—kebocoran gula rafinasi impor untuk industri yang diolah untuk gula konsumsi.
Rendemen dan produktivitas gula rendah. Itu bisa diatasi dengan bibit tebu yang unggul melalui pemuliaan tanaman. Hasilnya: 1) tebu yang tidak terpengaruh oleh iklim/musim, 2) tebu yang tahan terhadap berbagai penyakit, 3) tebu memiliki rendemen gula yang tinggi.
Sayangnya proses pemuliaan tanaman konvensional memakan waktu lama, bahan bisa sampai sepuluh (10) tahun. Solusinya pemuliaan tanaman dengan menggunaan radiasi.
Prinsip dasarnya, radiasi akan mengakibatkan mutasi; mutasi untuk meminimalisasi sifat yang tidak diinginkan dan atau memunculkan sifat unggul dari tanaman tebu—misalnya lebih tahan penyakit dan produktivitasnya lebih tinggi. Radiasi biasanya menggunakan sinar gamma.
Menurut International Atomic Energy Agency (IAEA) pemuliaan tanaman melalui proses mutasi bisa disebut mutation breeding. Mutation breeding tdak hanya menggunakan radiasi, namun bisa juga menggunakan bahan kimia.
Mutation breeding diawali dengan memberi perlakuan pada benih atau bagian tanaman lain dengan mutagen—zat yang menyebabkan mutasi; menyebabkan variasi genetik pada tanaman yang disebut mutan. Kemudian, mutan yang diinginan dipilih dan dikembangbiakkan.
Kapasitas mesin penggiling tebu yag kecil dan pabrik gula yang tua dan sedikit. Solusinya, tidak bisa tidak dengan melakukan investasi, mendirikan pabrik gula baru yang modern. Bisa juga, dengan melakukan peremajaan pabrik lama: mengganti mesin lama dengan mesin baru yang lebih besar kapasitas produksinya dan modern teknologinya.
Luas lahan tebu masih kurang. Penambahan luas lahan merupakan solusi. Namun perlu diperhatikan, penambahan luas lahan ini jangan sampai merusak lingkungan. Misalnya, membabat hutan lindung untuk perkebunan tebu. Barangkali kita bisa memanfaatkan lahan-lahan marjinal, diolah kembali, sehingga cocok untuk ditanami tebu.
Tataniaga gula yang belum baik. Persoalan utamanya yaitu kebocoran gula rafinasi impor untuk industri; diolah menjadi gula konsumsi; dijual ke pasar dan dikonsumsi masyarakat.
Solusinya, kebocoran gula rafinasi impor itu harus diselesaikan dengan baik dan tuntas, melalui penegakkan hukum yang tegas dan transparansi sistem tataniaga gula.
Jika tataniaga gula tidak diperbaiki, petani tebu akan terus dirugikan. Akibatnya, petani tebu menjadi enggan bahkan kapok menanam tebu. Tebu hasil panen petani tidak terserap oleh pabrik gula akibat masuknya gula rafinasi impor. Ditambah, harga dan kualitas gula konsumsi lokal kalah bersaing dengan gula konsumsi yang terbuat dari gula rafinasi impor. Itu bisa menyebakan lingkaran setan—ujungnya penambahan kuota impor gula rafinasi.
Garam memiliki persoalan yang serupa dengan gula. Kualitas garam nasional kita masih kurang bagus. Sehingga impor garam adalah pilihan yang tidak terelakkan.
Solusinya juga tidak jauh berbeda dengan gula: menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas produksi dalam negeri. Terlebih potensi produksi garam kita juga besar—memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Selain itu, tataniaga garam perlu diperbaiki. Sehingga kita bisa swasembada garam konsumsi, bahkan garam industri.
Contoh komoditas pangan lainnya, yaitu jagung. Menurut Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (PDSIP) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2024—“Analisis Kinerja Perdagangan Jagung”—produksi jagung Indonesia tahun 2023 mencapai 14,46 juta ton atau turun 12,5 persen dari produksi jagung tahun 2022. Harga jagung di tingkat produsen tahun 2023 yaitu Rp. 5.360/kg, tingkat konsumen pedesaan Rp. 7.937/kg dan kecenderungan terus meningkat.
Turunnya produksi jagung nasional membuat harga jagung di konsumen pedesaan mengalami kenaikan dan terus melakukan impor jagung. Itu sejalan dengan data yang disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (rri.co.id, 26/12/2024): Indonesia sepanjang Januari-November 2024 masih terus melakukan impor jagung 1.3 juta ton. Sebagian besar jagung impor tersebut dimanfaatkan untuk industri. Selama tiga tahun terakhir hanya sebagian kecil saja untuk ternak—sekitar 17% (UN Comtrade).
Menurut perhitungan pemerintah, tahun 2025 kita bisa swasembada jagung. Namun itu bisa meleset jika tekad pemerintah untuk menyetop jagung untuk pakan ternak gagal. Apalagi, jika kalkulasi panen jagung tidak sesuai target. Mengingat produksi jagung kita fluktuatif—menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), selama 6 tahun terakhir, panen jagung kita mengalami fluktuasi berkisar 18-22 juta ton.
Solusinya, ekstensifikasi pertanian jagung mungkin bisa dilakukan namun harus dengan bijaksana—meminimalisasi kerusakan lingkungan dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian marjinal, di luar Jawa khususnya.
Selain itu, pemuliaan tanaman untuk menghasilkan bibit jagung yang unggul harus terus dilakukan. Sehingga jagung kita lebih tahan terhadap penyakit, tidak terpengaruh dengan perubahan cuaca/iklim, dan produktivitasnya tinggi.
Satu hal penting lainnya yaitu, melakukan sinkronisasi data terkait pertanian jagung oleh pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Apa yang sudah dilakukan saat ini perlu diapresiasi, namun itu bisa ditingkatkan lagi. Terlebi saat ini eranya teknologi informasi.
Kesimpulannya, kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor beras, gula konsummsi, garam konsumsi, dan jagung perlu mendapatkan apresiasi. Itu merupakan salah satu bentuk keseriusan dalam mewujudkan swasembada pangan.
Namun kebijakan itu akan lebih baik jika diikuti dengan analisa dan perencanaan yang mendalam dan detail terkait apa yang akan dilakukan. Khususnya, mengurangi dampak negatif penghentian impor bahan pangan beras, gula, garam, dan jagung. Sembari melakukan langkah yang terencana dan terukur pencapaian target swasembada pangan tersebut. Tidak lupa, melibatkan teknologi terkini untuk melakukan perbaikan tataniaga komoditas pangan.
—
*) BOIMIN PhD, Direktur Eksekutif the Banana Institute: Center for Food Policy, and Food for Health & Wellness, menyelesaikan S3-Ilmu Pangan di University of Massachusetts Amherst