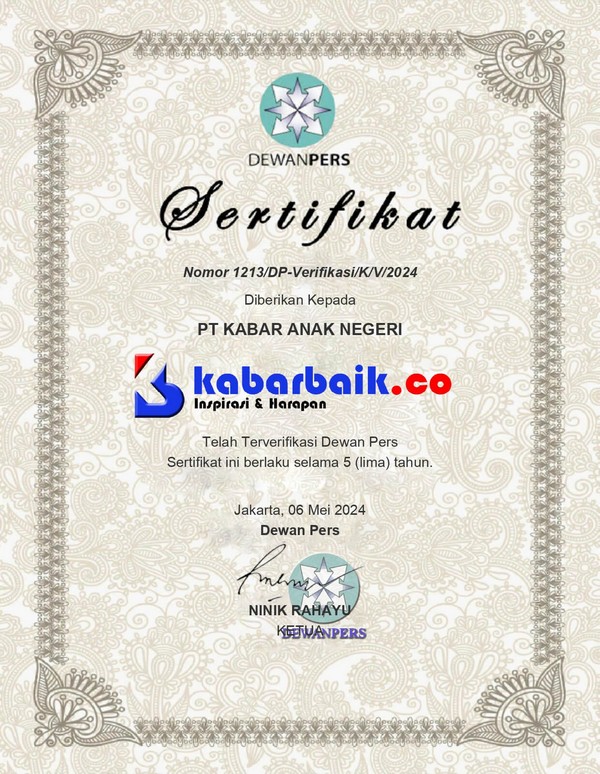PEMERINTAH Indonesia memikul tanggung jawab besar dalam membina kehidupan keagamaan umat. Namun, belakangan langkah-langkah komunikasi yang diambil terkadang menimbulkan kerisauan. Salah satu yang paling mencolok adalah keterlibatan influencer media sosial (medsos) dalam narasi dan promosi penyelenggaraan ibadah haji.
Sekilas, strategi ini tampak progresif. Menyesuaikan diri dengan zaman digital, menyasar generasi muda, dan mengemas pesan keagamaan agar lebih relatable. Tapi, jika ditelusuri lebih dalam, langkah ini menyimpan paradoks dan risiko yang tak bisa diabaikan: Apakah pemerintah sedang mengorbankan kedalaman spiritualitas demi engagement dan popularitas semu?
Pertama, kedangkalan narasi dan ancaman misinformasi. Haji bukan sekadar perjalanan fisik ke Tanah Suci. Ia adalah puncak perjalanan spiritual, dengan tuntunan syariat yang rumit dan pengalaman batin yang dalam. Maka, menjadi ironi ketika narasi haji lebih sering dibungkus dalam kisah belanja-belanja, kamar hotel bintang, atau outfit-of-the-day (OOTD).
Influencer, seberapa pun banyak pengikutnya, umumnya tidak dibekali kompetensi keilmuan soal manasik, fikih haji, atau bahkan konteks sosial-psikologis jemaah. Ketika pengalaman subjektif mereka diposisikan sebagai representasi umum, maka terjadilah reduksi makna dan potensi misinformasi. Apakah pemerintah siap menanggung risikonya?
Kedua, kesan komersialisasi ibadah, hilangnya nilai ketawaduan. Ada yang tercerabut dari esensi ketika ibadah dijadikan komoditas visual. Haji bukan festival gaya hidup. Bukan pula panggung konten viral. Namun, justru demikianlah kesan yang tergambar dari banyak unggahan influencer yang dilibatkan. Estetika dikedepankan, spiritualitas ditinggalkan. Engagement didahulukan, ketulusan kerap dikorbankan.
Ini bukan soal alergi terhadap teknologi atau media sosial. Namun, soal bagaimana kita memuliakan ibadah, menjaga kesuciannya, dan memastikan bahwa publik mendapatkan gambaran yang utuh, tidak bias, tidak glamor, apalagi sampai menyesatkan.
Ketiga, delegitimasi otoritas dan krisis kredibilitas. Pemerintah memiliki otoritas keagamaan yang sah dan formal. Tapi, saat influencer menjadi corong utama informasi publik, maka terjadi pergeseran persepsi. Masyarakat tak lagi menjadikan ulama atau petugas resmi sebagai rujukan utama, melainkan ”public figure” yang lebih terdengar karena algoritma. Ini bukan cuma persoalan komunikasi, melainkan soal integritas.
Apakah institusi pemerintah rela “menitipkan dakwah” kepada mereka yang belum tentu menguasai ilmunya? Maka, seperti dalam sebuah ayat: Tunggulah saatnya….
Keempat, efektivitas anggaran publik. Undangan, akomodasi, fasilitas, bahkan honorarium influencer jelas memakan anggaran. Tapi, apa dampaknya terhadap peningkatan pemahaman umat? Apakah lebih banyak jemaah memahami rukun haji, hikmah, dan nilai-nilai yang terkandung di baliknya? Atau justru lebih banyak yang mengira haji adalah sekadar pengalaman eksklusif berbiaya mahal?
Anggaran publik seharusnya diarahkan pada program-program edukatif dan peningkatan layanan, bukan sekadar mengejar metrik viralitas yang semu dan temporer.
Kelima, sumber daya internal termarginalkan. Ironisnya, pemerintah sebenarnya sudah memiliki pasukan informasi yang jauh lebih kredibel. Sebut saja, para penyuluh agama, petugas haji berpengalaman, dan ulama yang memahami syariat. Ditambah dengan media profesional yang memegang etika jurnalistik. Tapi, semua itu kerap kalah gaung oleh satu unggahan Instagram Story atau TikTok dari influencer yang tidak tahu beda antara tawaf dan sai, nafar awal dan nafar tsani, wukuf dan safari wukuf, mabit dan tarwiyah.
Mengapa potensi internal itu tidak diberdayakan secara optimal? Mengapa suara yang sah secara syariat dan pengalaman justru tidak diprioritaskan? Malah terefesiensikan.
Jika pemerintah memang ingin menjangkau generasi digital, langkahnya tetap bisa canggih tanpa harus kehilangan ruh. Beberapa alternatif yang lebih substansial bisa dilakukan. Pertama, gandeng sebanyak mungkin wartawan kompeten dan media-media profesional yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Bekali dan berikan akses kepada jurnalis yang kompeten itu untuk meliput proses haji secara komprehensif. Mereka memiliki kemampuan untuk menggali narasi-narasi yang edukatif, substantif, dan objektif.
Kedua, berdayakan penyuluh dan tokoh agama lokal. Mereka adalah pilar komunikasi di lapangan. Bekali mereka dengan materi terbaru dan platform untuk berbicara ke publik. Ketiga, bangun kanal resmi yang interaktif dan terpercaya. Website, media sosial, aplikasi hingga podcast resmi, semua bisa menjadi saluran informasi utama, asalkan dikelola dengan standar profesional.
Keempat, produksi konten yang edukatif berkualitas tinggi. Narasi kuat bisa viral dengan sendirinya. Gunakan wajah-wajah yang memang kredibel di bidangnya, bukan sekadar terkenal. Yang utama dan paling utama adalah fokus pada layanan. Layanan yang baik akan menciptakan testimoni alami dari jemaah. Biarkan mereka jadi penyampai pesan yang otentik.
Pemerintah tentu boleh berinovasi. Namun, jangan sampai inovasi mengebiri esensi. Jangan sampai syiar tenggelam oleh sensasi. Jangan sampai ibadah sebesar haji diturunkan martabatnya menjadi sekadar konten untuk ditonton, bukan untuk direnungkan kemudian kehilangan makna. Jangan sampai kelak masyarakat tidak memahami haji qiran, haji tamattu, haji ifrad, dan sejenisnya, tetapi lebih kenal dengan haji influencer.
Ibadah bukan panggung. Dan kementerian atau lembaga terkait tentu bukan manajemen artis. (*)