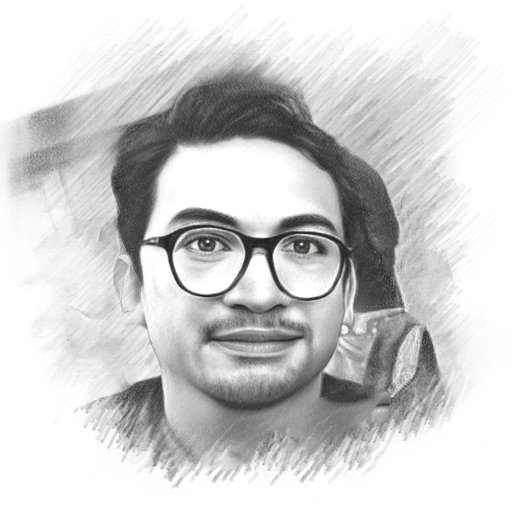OLEH: ANGGIT SATRIYO NUGROHO*)
SEBENTAR lagi, makan bergizi akan diluncurkan sebagai program negara. Untuk seluruh siswa di Indonesia.
Apa sudah begitu susahnya rakyat Indonesia, sampai makan saja harus diurus negara. Bagi sebagian orang mungkin akan menganggapnya begitu. Toh, selama ini tanpa cawe-cawe negara, selama bertahun-tahun lamanya, rakyat Indonesia sudah rutin makan. Apalagi kalau mereka datang dari keluarga yang berkecukupan.
Tapi, bagi jutaan siswa yang lain, urusan makan ini persoalan tersendiri. Makan itu menjadi sesuatu yang istimewa. Bisa rutin sarapan saat akan berangkat bersekolah itu “sesuatu” banget. Terlebih apabila mereka menyantap sarapan yang bergizi.
Ingatan saya terlempar berbilang tahun lalu. Saat masih belajar dari bangku SD hingga SMA di Ngawi.
Bisa sarapan dengan baik itu luar biasa. Bagi ibu rumah tangga Indonesia, bisa rutin menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya perjuangan yang tak mudah. Itulah wujud nyata kasih seorang ibu kepada anaknya ketika akan memulai hari.
Setidaknya sarapan itu akan menjadi bekal energi para siswa Indonesia ketika harus menyerap pelajaran dari gurunya.
Pada masa itu, ibu saya selalu bangun pagi mencarikan sarapan untuk anaknya. Kalau tidak sempat memasak, maka menu utama yang disantap adalah nasi pecel. Penjualnya bernama Yuk Mi. Hanya berjarak lima rumah, dari tempat saya tinggal. Karenanya, jangan heran ibu saya selalu mendapat nomor pertama saat mengantre nasi pecel itu.
Yuk Mi adalah penjual nasi pecel legendaris di desa saya tinggal. Saat pagi buta itu, dia sudah siap dengan nasi kemebul yang ditaruh dalam bakul bambu. Lengkap dengan kulupan dan bumbu pecelnya yang gurih, kental dan manis. Plus dua iris tempe kemul. Bagi saya, itulah sarapan wajib selama bertahun tahun lamanya. Dari SD hingga SMA.
Kini Yuk Mi sudah sepuh. Tapi, tetap berjualan nasi pecel. Panggilannya sudah tidak lagi Yuk, sebagaimana saat dia muda. Karena sudah memiliki banyak cucu, panggilannya berubah Mbah Mi. Kulitnya mulai keriput. Badannya ringkih. Tapi, rasa pecelnya tak berubah. Tetap lezat disantap pagi buta.
Nasi pecel Yuk Mi tetap murah. Hanya Rp 4 ribu. Ada perdebatan di publik. Negara hanya mengalokasikan Rp 10 ribu untuk makan gratis siswa. Saya yakin dengan unit cost yang berlebih itu, nilai gizinya akan bertambah.
Nasi pecel Yuk Mi bisa murah karena memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Berasnya diolah dari sawahnya sendiri. Kacangnya beli dari tetangga. Kulupannya juga diolah dari tanaman para tetangga. Yang dibelinya dengan harga murah juga. Bungkusnya daun jati yang setiap hari diantarkan oleh pemetik daun yang tinggal di pinggir hutan milik Perhutani.
Satu ketika, saat saya pulang kampung, saya merasakan lezatnya nasi pecel Yuk Mi lagi. Sesekali dia berseloroh kepada pengunjung warungnya. “Nasi pecel saya ini sudah mengantarkan anak-anak desa ini jadi sarjana semua,” katanya.
“Ada yang lulusan ITS, ada yang lulusan Unair, ada yang perwira Angkatan Laut, ada yang perwira Angkatan Darat. Semua yang jadi orang itu, saat sekolah sarapan di sini semua,” katanya.
Meriung mengitari meja adalah orang-orang yang sudah bertahun-tahun langgangan nasi pecelnya. Mereka adalah orang-orang yang dibsarkan dari nasi pecel. Ada kapolsek, dokter kepala sekolah, hingga kontraktor.
Satu kali, satu desa heboh bukan kepalang. Warung pecel Yuk Mi tutup seminggu lebih. Rupanya, suaminya harus opname di rumah sakit. Kena stroke.
Gara-gara itu bisa dipastikan entah berapa siswa yang tidak sarapan pagi.
Bagi warga desa, Yuk Mi adalah pejuang gizi. Legacynya banyak, konsistensinya dibangun bertahun-tahun dan nyata.
Sarapan memang istimewa. Bayangkan, jika pagi itu tidak sarapan, lalu siswa harus mengikuti upacara bendera. Yang banyak terjadi adalah pingsan ketika upacara berlangsung. Semaput orang Ngawi bilang.
Betapa pentingnya sarapan. Bayangkan pula, ketika pada jam pertama belajar harus menyerap mata pelajaran fisika atau matematika. Tentu saja, baru seperempat jam sang guru berbicara, para siswa sudah banyak menguap. Pikirannya tidak nyambung. Gurunya pun marah-marah. Setiap hari begitu. Para siswa itu tentu akan sulit bersaing dengan siswa yang lebih siap. Yang dari rumahnya sudah dibekali para ibunya sarapan. Jika kondisi itu terjadi di banyak siswa di Indonesia, maka mereka akan mengalami ketinggalan daya serap ilmu secara masal.
Ujungnya tentu daya saing SDM kita rendah. Bayangkan, daya saing kita pada 2023 masih di papan bawah berdasar riset International Institute for Management Development World Talent Ranking. Masih di peringkat 47 dari 64 negara lain di dunia.
Karenanya kerja kolaborasi dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing. Setidaknya, ada kesadaran bersama untuk mewujudkan peningkatan daya saing. Tentu faktor-faktor elementer yang mempengaruhi dari peran-peran kecil harus harus diapresiasi. (*)
—
*) ANGGIT SATRIYO NUGROHO, akademisi alumnus Unej dan Unair tinggal di Sidoarjo