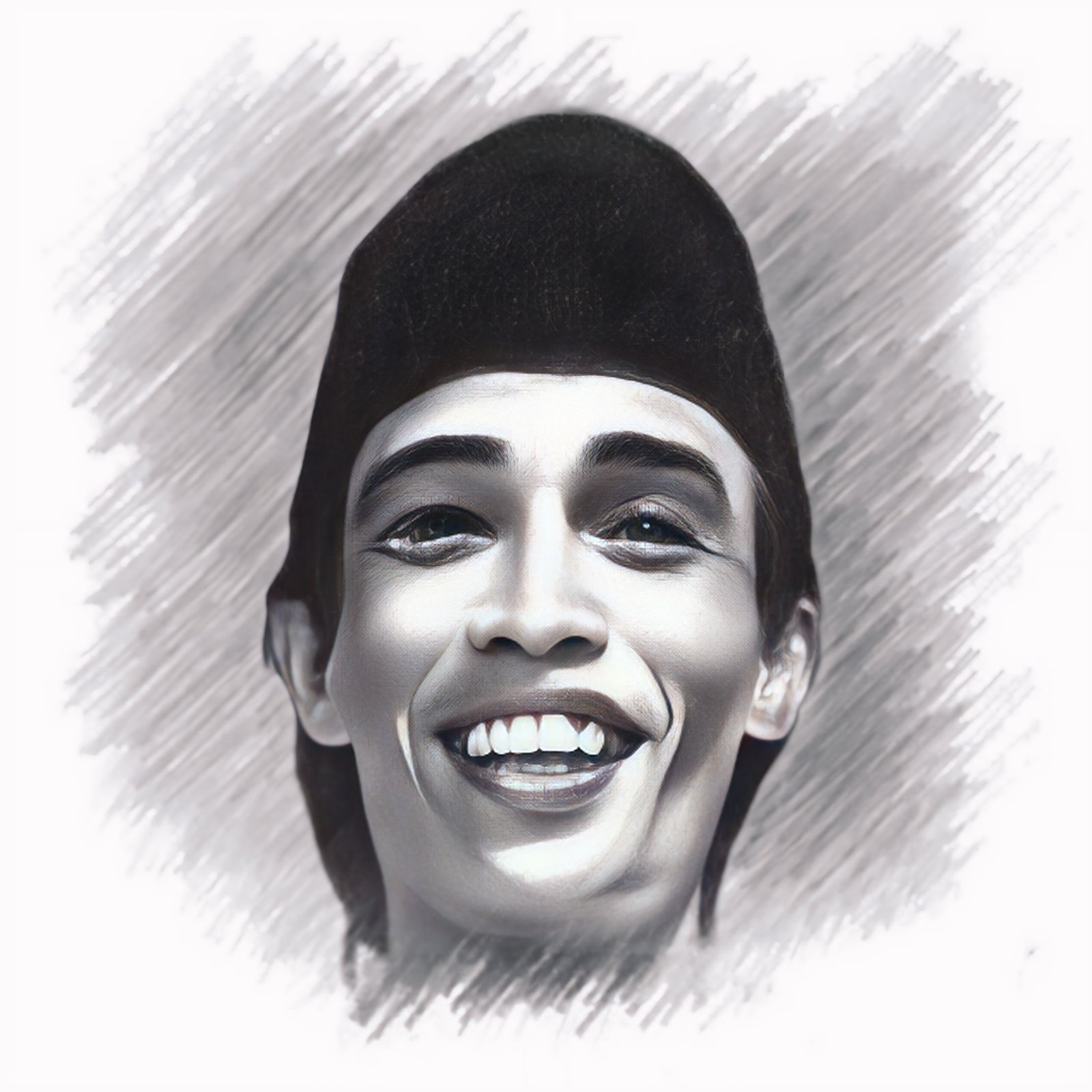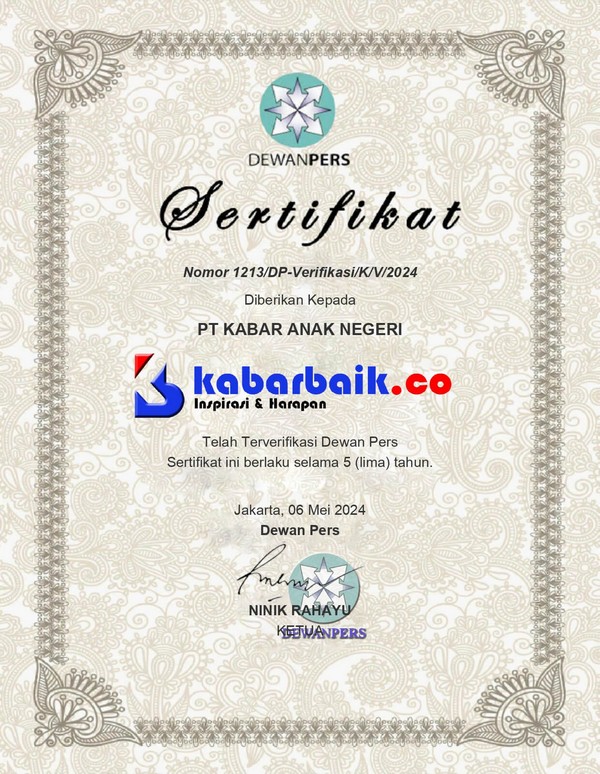OLEH: M. SHOLAHUDDIN SSi, MPSDM, CMC*)
WARGA Jawa Timur menghirup udara beracun dan minum air tercemar mikroplastik. Tanpa informasi terbuka, mereka tak berdaya menghadapi ancaman ini. Situasi tersebut menunjukkan betapa pentingnya keterbukaan informasi publik. Khususnya, informasi lingkungan yang menyangkut hidup orang banyak, bahkan lebih urgen dibanding perdebatan publik yang panjang soal keterbukaan informasi ijazah capres-cawapres itu.
—-
Setiap tanggal 28 September, dunia memperingati International Day for Universal Access to Information atau yang dikenal sebagai Right to Know Day. Peringatan ini pertama kali disepakati pada tahun 2002 di Sofia, Bulgaria, ketika organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara berkumpul untuk menegaskan kembali hak warga atas informasi. Sejak itu, tanggal ini diperingati secara global sebagai pengingat bahwa akses informasi merupakan hak fundamental setiap orang, sekaligus fondasi bagi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Tahun 2025, UNESCO mengusung tema “Ensuring Access to Environmental Information in the Digital Age.” Tema ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi lingkungan semakin penting di tengah derasnya arus digitalisasi. Informasi bukan hanya sekadar kumpulan angka, melainkan landasan bagi masyarakat untuk memahami kondisi sekitarnya, mengawasi kebijakan, hingga mengambil bagian dalam menjaga hak-hak dasar atas lingkungan yang sehat.
Konteks Jawa Timur memperlihatkan betapa isu ini amat relevan. Provinsi berpenduduk hampir 42 juta jiwa ini adalah pusat pertumbuhan industri, perdagangan, dan pembangunan. Namun, perkembangan tersebut dibarengi dengan tekanan serius terhadap lingkungan hidup. Data kualitas udara di Surabaya pada awal September 2025 mencatat indeks sekitar 124 AQI, masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.
Sepanjang 2024, penelitian akademis menunjukkan rata-rata konsentrasi PM2.5 di kota ini mencapai 36 µg/m³, dengan titik tertinggi di kawasan Kertajaya. PM2.5 sendiri adalah partikel halus di udara dengan ukuran tidak lebih dari 2,5 mikrometer—sekitar tiga puluh kali lebih kecil dari diameter rambut manusia—yang bisa masuk jauh ke saluran pernapasan hingga ke alveolus paru-paru, bahkan sebagian dapat menembus ke dalam aliran darah. Partikel ini umumnya berasal dari emisi kendaraan bermotor, asap industri, pembakaran sampah, hingga kebakaran lahan. Karena ukurannya yang amat kecil, keberadaannya sulit terlihat tetapi berisiko besar terhadap kesehatan, mulai dari gangguan pernapasan, iritasi pada mata dan tenggorokan, hingga peningkatan risiko penyakit kronis seperti jantung, stroke, dan kanker paru.
Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ambang batas aman rata-rata tahunan PM2.5 hanya 5 µg/m³, sementara batas harian adalah 15 µg/m³. Dengan demikian, angka 36 µg/m³ yang ditemukan di Surabaya jelas sudah melampaui ambang aman tersebut, menggambarkan betapa udara yang dihirup jutaan warga setiap hari membawa risiko serius bagi kesehatan.
Kondisi serupa terlihat pada sungai-sungai besar, terutama Sungai Brantas. Sungai sepanjang 320 kilometer ini menjadi sumber air baku utama bagi jutaan penduduk Jawa Timur. Namun, kajian Ecoton pada 2024 mengungkap bahwa hampir 90 persen ikan di Brantas mengandung mikroplastik, sementara lebih dari seratus titik bantaran sungai dipenuhi timbunan sampah plastik.
Kasus pencemaran juga muncul di beberapa daerah, mulai dari limbah berbahaya yang mencemari sungai hingga pembuangan limbah ternak perusahaan besar. Semua ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan bukan sekadar isu teknis, melainkan masalah nyata yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan paling dasar masyarakat. Yakni, air bersih, udara sehat, dan pangan yang aman.
Secara regulasi, landasan hukum keterbukaan informasi sebenarnya cukup kokoh. Undang-Undang (UU) No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebut dokumen lingkungan sebagai informasi yang wajib dibuka. Jawa Timur telah mengeluarkan Pergub No. 8/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Pergub No. 48/2015 tentang Tata Kelola Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik. Semua regulasi ini menegaskan bahwa informasi lingkungan bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh badan publik.
Namun, implementasi sering kali tidak sejalan dengan regulasi. Dokumen AMDAL, meski statusnya dokumen publik, kerap sulit diakses dengan alasan rahasia dagang, hak cipta atau alasan lainnya. Data kualitas udara mungkin memang telah tersedia di laman resmi, tetapi lebih banyak tersaji dalam bentuk teknis yang sulit dipahami masyarakat awam. Pembaruan data juga tidak selalu konsisten. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang progresif dengan praktik yang masih parsial, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi lingkungan belum sepenuhnya terpenuhi.
Beberapa daerah di Indonesia sebenarnya sudah mencoba melangkah lebih jauh. DKI Jakarta mengembangkan aplikasi pemantauan kualitas udara real-time yang terintegrasi dengan kebijakan uji emisi kendaraan. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menggunakan sistem pemantauan kebakaran hutan berbasis satelit yang bisa diakses publik. Praktik-praktik ini memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi bisa diwujudkan dengan memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat sipil juga berperan penting. Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jawa Timur telah mengungkap berbagai persoalan lingkungan, mulai dari pencemaran sungai hingga pengelolaan sampah plastik. Komunitas lokal berinisiatif mengelola bank sampah, memantau kualitas air sumur, dan mendorong transparansi anggaran lingkungan. Aktivitas semacam ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya soal dokumen resmi pemerintah, melainkan juga keterlibatan warga dalam menjaga lingkungannya.
Karena itu, badan publik di Jawa Timur perlu meneguhkan keterbukaan sebagai budaya kerja. Data kualitas udara seharusnya dipublikasikan dalam format visual yang mudah dipahami. Dokumen AMDAL harus dibuka tanpa hambatan administratif. Informasi tentang pencemaran industri maupun pengelolaan limbah harus tersedia secara transparan. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat memperluas dampaknya dengan menyebarkan hasil kajian ke publik. Media massa berperan sebagai penghubung, menyajikan data teknis menjadi informasi yang membumi bagi masyarakat luas.
Para kepala daerah, sebagai pengambil kebijakan utama, memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal ini. Mereka dapat mendorong pembangunan sistem pemantauan kualitas udara dan air secara real-time yang bisa diakses publik, memastikan dokumen AMDAL serta izin lingkungan dipublikasikan secara lengkap dan mudah dipahami, serta memberikan ruang bagi warga untuk ikut memantau kondisi lingkungan di sekitarnya. Selain itu, penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan harus transparan, sementara edukasi dan kampanye publik tentang risiko polusi dan pencemaran bisa menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang memadai untuk menjaga kesehatan dan lingkungan. Dengan pendekatan seperti ini, kepala daerah tidak hanya melindungi warganya, tetapi juga membangun budaya tata kelola lingkungan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Right to Know Day menjadi cermin apakah hak masyarakat atas informasi benar-benar dihormati. Lingkungan bukan persoalan abstrak, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari: udara yang dihirup, air yang diminum, pangan yang dikonsumsi. Menutup informasi berarti mengabaikan hak dasar masyarakat untuk hidup sehat. Sebaliknya, membuka informasi berarti membuka jalan bagi tata kelola lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Jawa Timur, dengan posisinya sebagai simpul penting penghubung Indonesia bagian Barat dan Timur, memiliki peluang besar untuk menjadi teladan dalam keterbukaan informasi, terutama lingkungan. Jika keterbukaan dijadikan pedoman, provinsi ini dapat melangkah lebih jauh, tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai wilayah yang menjamin masa depan sehat bagi Generasi Emas 2045. (*)
—
*) M. SHOLAHUDDIN, Komisioner Komisi Informasi Provinis Jawa Timur