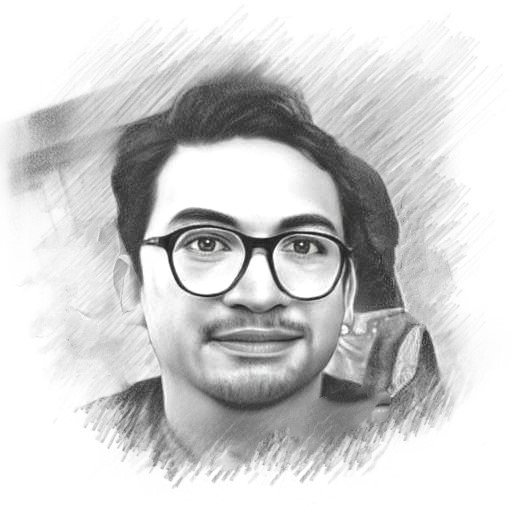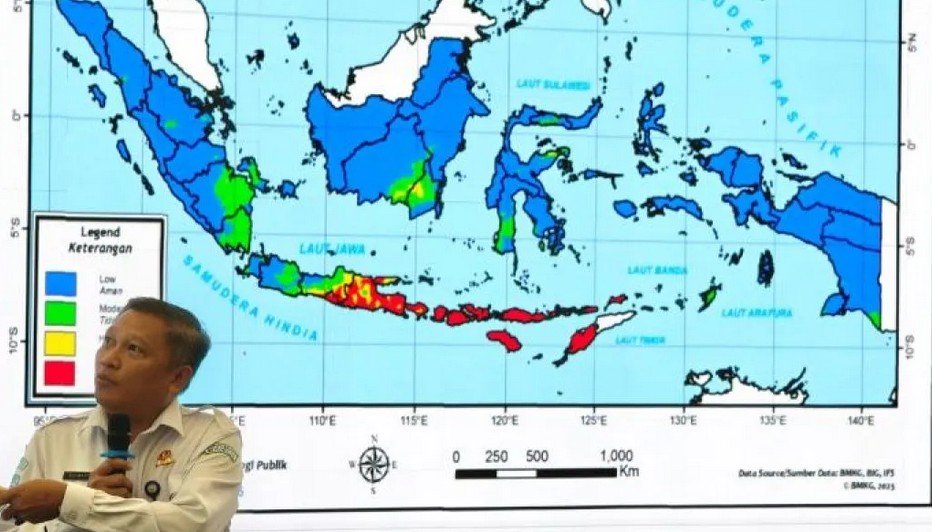OLEH; ANGGIT SATRIYO NUGROHO*)
SEORANG siswa terlihat jengkel kepada temannya di satu sekolah. Beberapa kali ia mengajarkan cara mengerjakan mata pelajaran matematika. Tapi, teman itu tak juga paham. Ia pun berkata : “Kebanyakan makan ketela kamu itu,” kata siswa tadi bersungut-sungut.
Ketela termasuk bahan pangan termurah di negeri ini. Di tanah tandus pun, ketela bisa bertahan hidup. Sampai-sampai ketela digunakan untuk mengibaratkan makanan kurang gizi yang dampaknya tak bisa digunakan untuk berpikir.
Terlebih lagi, bila Anda tinggal di daerah dengan tanah yang subur. Ketela yang ditanam akan menghasilkan buah yang empuk bila dikukus.
Di beberapa daerah, ketela juga menjadi bahan pangan pengganti beras. Itu terjadi bila harga beras tak terjangkau lagi. Orang desa pun bersiasat untuk menghemat beras. Nasi pun dicampur dengan ketela. Jadilah nasi tiwul. Hanya lidah kita saja yang terbiasa makan nasi. Kendati sebenarnya makan nasi tiwul juga terasa enak. Terlebih lagi bila ada sambal.
Kebetulan hidup saya tak jauh-jauh dari ketela. Bahkan, bisa dibilang setiap hari dari SD sampai SMA semasa tinggal di Ngawi setiap hari melihat ketela.
Kebetulan saya bertetangga dengan majikan gaplek. Anda tahu, gaplek adalah ketela yang sudah dikupas dan dijemur. Di desa biasanya warga menjemur ketela. Bisa dimana saja. Di pelataran rumah. Bahkan, agar mendapatkan panas, terkadang ketela juga dijemur di atas genting.
Biasanya penghasil gaplek adalah daerah-daerah tandus. Lahan mereka kesulitan air. Bertanam padi tak memungkinkan. Maka, yang cepat menghasilkan dan tidak berisiko adalah bertanam ketela.
Bertruk-truk gaplek dari masyarakat ditampung lalu dikirimkan ke pabrik tepung tapioka. Gaplek juga dikirim ke pabrik makanan kecil sebagai bahan dasar olahannya.
Bertani ketela sempat mencapai kejayaan pada akhir 90-an. Hampir semua orang bertanam ketela. Pabrik tepung tapioka pun berdiri dimana-mana. Bahkan, di era Soeharto, Indonesia sempat jadi pengekspor tapioka. Tapi, masa keemasan itu tidak lama. Cukong menghancurkan harga ketela. Banyak warga desa yang bertanam ketela akhirnya ogah memanennya.
Maka, saya bisa memahami unjuk rasa ribuan para petani di Lampung. Mereka protes karena ketela yang ditanam di lahan-lahan minim air itu tak terserap oleh pabrik tepung tapioka setempat.
Pabrik hanya mau membeli kalau harga per kilogram ketela tidak lebih dari seribu rupiah. Padahal, sebelumnya harga ketela pernah sangat bagus, yakni mencapai Rp 2 ribu.
Anda bayangkan, makan apa para petani ketela itu akhirnya. Sebab, harga penjualan ketela yang dirawatnya berbulan-bulan tidak menghasilkan apa-apa.
Bagi petani yang hidup di lahan sulit air, bertani ketela adalah satu-satunya penghidupan. Mereka bisa makan sehari-hari, beli token listrik, bayar pajak kendaraan semuanya berasal dari sana.
Usut punya usut, harga ketela di Lampung jatuh lantaran ketela lokal harus bersaing dengan beredarnya ketela impor.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman pun marah besar karena ini. Akademisi yang juga dikenal sebagai tokoh petani itu menyebut bahwa para pengimpor ketela itu tidak punya patriotisme.
Tentu saja kemarahan Amran di depan para wartawan tak boleh sekadar pemanis belaka. Ia tak boleh terlihat marah di depan publik, lantas di belakang tak berbuat apa-apa. Apalagi selama ini kita sudah menggariskan kebijakan ketahanan pangan yang pro petani.
Semua petani berharap Presiden Prabowo Subianto dan Mentan Amran Sulaiman yang dikenal tegas bisa bertindak. Sebagai pemegang wewenang, ia harus bisa mengambil kebijakan yang bisa menormalisasi harga ketela tadi. Indikator bahwa kebijakan Amran sudah berjalan sangat gampang. Setidaknya, bila ketela lokal kembali terserap lagi. (*)
—
*) ANGGIT SATRIYO NUGROHO, Akademisi, alumnus Pascasarjana Unair