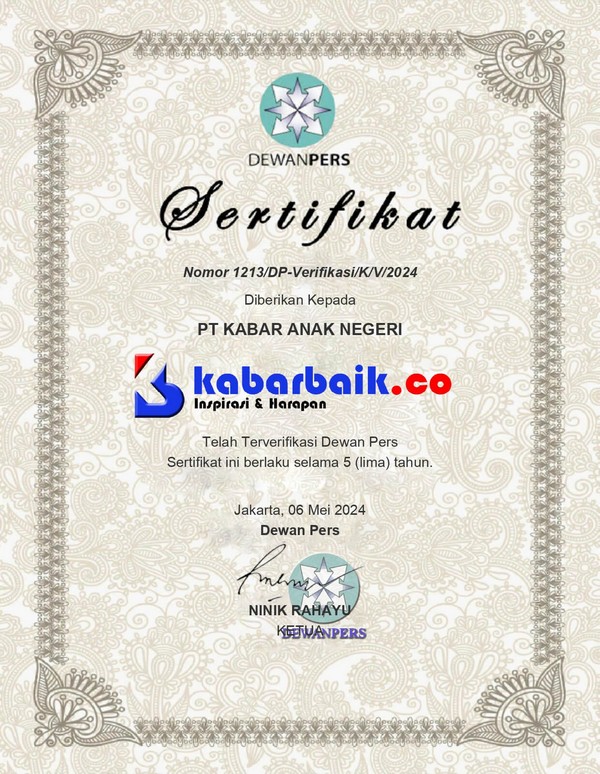DI ATAS kertas, program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah narasi kemanusiaan yang indah. Suci dan mulia. Negara hadir memberi makan bagi anak-anak bangsa. Gizi terpenuhi, masa depan terjamin. Tak peduli miskin ataupun kaya. Namun, di balik narasi itu, dalam implementasinya publik masih menemukan masalah. Kasus keracunan, ketidaksiapan, dan indikasi bagi-bagi ’’proyek’’ di balik progam MBG.
Karena itu, belakangan terdengar pula narasi sumbang dari sudut lain bahwa alih-alih orkestra gizi yang simfoni. Yang terdengar justru nada-nada birokrasi yang seolah gagap. Anggaran besar bagai air bah yang tampaknya belum jelas muaranya. Sebuah pertanyaan besar pun menggantung di udara, setebal kabut ketidakpercayaan yang mulai menyelimuti niat baik dari program ini.
Bayangkanlah, program mulia ini diibaratkan sebuah lukisan agung tentang anak-anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Kelak menjadi generasi emas. Namun, kanvasnya belum terbentang sempurna. Bahkan, terlipat di beberapa sudut, menyisakan keraguan akan luas bidang yang akan digarap. Catnya tercecer di lantai kuasa, diinjak oleh kaki-kaki kepentingan yang berlalu lalang, meninggalkan noda yang sulit dihilangkan. Dan tangan-tangan yang akan melukisnya justru sibuk berebut kuas, bukan untuk menciptakan harmoni warna, melainkan untuk mengklaim dominasi atas palet kuasa.
Bukankah ironis, sebuah gagasan luhur justru terancam layu sebelum berkembang, tergerogoti oleh ego dan kepentingan sesaat, seperti bunga indah yang diinjak sebelum merekah?
Filosofi mendasar sebuah negara hadir adalah melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Memberi makan anak-anak adalah investasi peradaban yang tak ternilai harganya, sebuah benih harapan untuk masa depan bangsa.
Namun, cara negara mewujudkan cita-cita ini patut direnungkan lebih dalam. Diuji dengan kaca mata etika dan nurani. Apakah keberpihakan yang tulus tercermin dalam perencanaan yang tergesa-gesa dan penuh tanda tanya, seolah membangun rumah impian tanpa cetak biru yang jelas? Ataukah ini sekadar panggung politik, di mana retorika kemanusiaan digunakan untuk kepentingan duniawi?
Kita belajar dari alam, bahwa setiap benih membutuhkan tanah yang subur, air yang cukup, dan perawatan yang telaten untuk tumbuh menjadi pohon yang kuat dan berbuah. Begitu pula dengan program ini. Jika fondasinya rapuh, dibangun di atas pasir ketidakjelasan dan keraguan, implementasinya serampangan, seperti angin yang menerbangkan debu tanpa arah yang pasti. Pengawasannya lemah, bagai pagar bambu yang mudah diterjang hewan buas, maka buah yang dihasilkan kelak bisa jadi pahit dan mengecewakan, meninggalkan rasa getir di lidah harapan.
Maka, mari kita telaah kembali “narasi kemanusiaan yang indah” ini dengan mata yang lebih jernih. Mata setajam elang yang mengawasi mangsanya dari ketinggian. Bukan untuk mencela dengan dengki, melainkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah rakyat yang dialokasikan benar-benar bermuara pada perut kenyang dan senyum cerah anak-anak Indonesia. Bukan pada pundi-pundi kuasa atau proyek-proyek yang menguntungkan sekelompok pihak. Orang dekat atau orang dalam. Bukan untuk meruntuhkan mimpi tentang generasi emas, tetapi untuk membangunnya di atas fondasi yang kokoh, transparan, dan akuntabel, seperti membangun istana di atas batu karang yang kokoh diterjang ombak zaman.
Kemuliaan sebuah program terletak bukan hanya pada retorikanya yang memukau, Yang bisa menghipnotis pendengar dengan janji-janji surga, tetapi pada implementasinya yang sungguh-sungguh memuliakan. Yang terasa nyata manfaatnya, bagi setiap anak bangsa. Kita tidak butuh retorika kosong yang bergema tanpa substansi, kita membutuhkan tindakan nyata yang mengubah nasib anak-anak menjadi lebih baik.
Sah-sah saja kalau ada yang mempertanyakan filosofi di balik pemberian MBG ini. Apakah ini sekadar sedekah sesaat yang menghilangkan lapar hari ini, namun tidak menyelesaikan akar permasalahan besok? Ataukah ini bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, yang mampu bersaing dan membawa bangsa ini ke puncak kejayaan? Jika hanya yang pertama, maka program ini tak lebih dari pemadam kebakaran sesaat. Yang membiarkan bara kemiskinan dan ketidakadilan terus membara di bawah permukaan.
Kita harus belajar dari sejarah, dari berbagai program serupa yang pernah ada. Mana yang berhasil dan mana yang gagal? Apa saja faktor penentunya? Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama, terjebak dalam euforia sesaat tanpa evaluasi yang mendalam. Program MBG harus menjadi momentum untuk perbaikan sistem, bukan sekadar proyek mercusuar yang megah di luarnya namun rapuh di dalamnya.
Evaluasi total adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Kita perlu menelisik setiap detail, mulai dari perencanaan yang matang, sumber pendanaan yang jelas dan tidak membebani rakyat, mekanisme distribusi yang efisien dan tepat sasaran, hingga pengawasan yang ketat dan transparan. Libatkan semua pihak, dari ahli gizi, pendidik, ekonom, hingga masyarakat sipil, agar program ini benar-benar menjadi milik seluruh bangsa, bukan hanya segelintir pihak.
Ingatlah, anak-anak adalah amanah terbesar bangsa ini. Masa depan mereka adalah masa depan Indonesia. Jangan sampai kita mempermainkan nasib mereka dengan program yang tidak matang dan penuh kepentingan terselubung. Mari kita wujudkan “narasi kemanusiaan yang indah” ini menjadi kenyataan yang membanggakan, bukan sekadar ilusi yang menyesatkan. Sebab, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga dan memelihara setiap anak bangsanya dengan sebaik-baiknya.
Sejak diluncurkan Januari 2025 lalu, beberapa kasus keracunan terjadi. Memang tidak salah, seperti kata kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa jumlah anak keracunan mungkin hanya nol koma sekian persen dari mereka yang aman-aman saja. Namun, tentu nasib anak bukanlah angka-angka matematika yang bisa dipersantase. Satu nyawa seorang anak tentu tak ternilai harganya karena di dalamnya terdapat harapan, cinta, dan kemungkinan tak terbatas.
Mencegah Kemudaratan Lebih Diutamakan
Dalam program MBG, rasanya penting untuk kita mengingat sebuah kaidah fikih. Mencegah kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kebajikan. Benar bahwa tujuan dari program ini baik dan mulia. Termasuk sebuah kebajikan. Namun, menghindari kerusakan (darar), lebih utama daripada menarik manfaat. Alasannya, pertama, kemudaratan (bahaya) bersifat nyata dan langsung merugikan, sementara kebaikan yang diharapkan bisa jadi tidak terwujud. Contoh, membiarkan seorang pencuri bebas, tanpa dihukum, karena alasan kasihan justru akan mendorong lebih banyak pencurian. Hukuman (mencegah kemudaratan) lebih penting daripada memberi belas kasih (kebajikan), karena dampaknya lebih luas.
Kedua, kerusakan lebih sulit diperbaiki daripada kehilangan kebaikan. Kebaikan yang terlewat bisa dicari lagi, tetapi kerusakan yang terjadi seringkali permanen. Contoh, lebih baik menolak proyek pembangunan yang merusak lingkungan (mencegah kerusakan alam) daripada membiarkannya demi lapangan kerja (kebaikan ekonomi), karena kerusakan alam bisa bersifat irreversible.
Ketiga, prinsip kehati-hatian (precautionary principle). Dalam Islam, kaidah dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih ini sejatinya menekankan bahwa kehati-hatian lebih utama daripada risiko. Contoh, lebih baik tidak makan jika makanan itu meragukan kehalalannya (mencegah kemudaratan) daripada memakannya dengan niat yang penting kenyang (kebajikan).
Jadi, kebaikan itu penting, tetapi jika harus memilih, mencegah bahaya harus didahulukan karena dampaknya lebih luas dan seringkali tidak bisa dikompensasi. Lebih baik kehilangan peluang baik daripada menanggung kerusakan yang buruk.
Tentu, kita semua tidak ingin dan tidak berharap bahwa makan bergizi gratis dengan narasi mulia ini, justru menjadi makan ‘’beracun’’ gratis. Baik beracun dalam makna sesungguhnya, yakni membuat daftar anak keracunan makin banyak, ataupun beracun dalam makna kiasan seperti menebarkan ’’racun’’ korupsi, kolusi, dan nepotisme baru. (*)