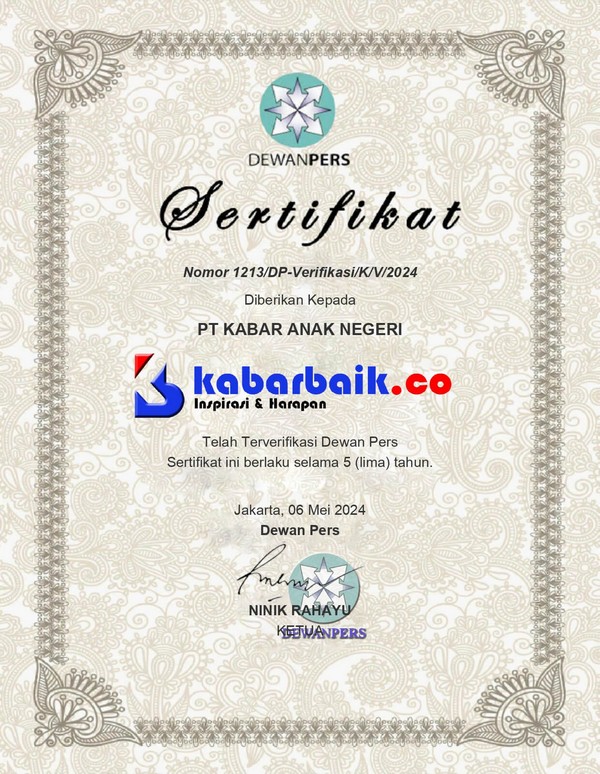SKANDAL di Pertamina. Kita hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Sembari menggerutu dan bergelayut ribuan tanya tak terjawab. Kok bisa? Orang dengan gaji miliaran per bulan, masih kekurangan? Berarti, sejatinya mereka miskin? Kok tega-teganya ’’menipu’’ masyarakat dengan mengoplos Pertalite menjadi Pertamax? Dan, pertanyaan kok dan kok lainnya. Kita yang terkadang sudah mules berfikir nasib sendiri, akhirnya pasrah. Bah, sakkarepmu!
Megakorupsi. Kerugian negara sangat fantastis. Mencapai Rp 193,7 triliun. Angka ini disebut Kejagung hanya dalam kurun setahun saja. Melihat angka ini, kita pun mules lagi. Andaikan uang segitu dibagikan kepada warga miskin se-Indonesia, masing-masing mendapatkan Rp 7,8 juta. Data dari BPS, jumlah warga miskin di Indonesia sekitar 22 juta jiwa. Kali lima tahun, per otang kebagian Rp 35 jutaan. Kalau sejak Pertamina berdiri? Rasanya selesai. Ini cuma dari perhitungan kerugian jual-beli BBM saja.
Tapi, tentu hitungan tersebut tidak absolut. Yang jelas, skandal itu menjadi bukti nyata betapa rapuhnya sistem transparansi dan akuntabilitas di lembaga publik. Salah satu faktor kunci yang memicu skandal ini adalah terjadinya asimetri informasi. Yaitu, ketimpangan akses informasi antara pihak internal (manajemen Pertamina) dengan eksternal (publik, regulator, dan pemerintah).
Asimetri informasi terjadi ketika salah satu pihak memiliki informasi lebih banyak daripada pihak lain. Ada ketidakberimbangan. Satu pihak memiliki akses ke informasi yang lebih baik atau lebih lengkap, dibandingkan dengam pihak lainnya. Konsep ini diperkenalkan dalam teori ekonomi informasi oleh George Akerlof, Michael Spence, dan Joseph Stiglitz, yang memenangkan Nobel Ekonomi tahun 2001.
Menurut teori mereka, asimetri informasi bisa menyebabkan pemilihan yang tidak menguntungkan karena kurangnya informasi (Adverse Selection), seseorang bertindak ceroboh karena merasa memiliki informasi atau perlindungan yang lebih baik (Moral Hazard), dan pasar atau sistem tidak berjalan optimal karena informasi yang tidak merata (Market Failure).
Dalam pemerintahan, asimetri informasi terjadi ketika pemerintah memiliki akses terhadap informasi kebijakan, keuangan, dan hukum yang lebih luas dibandingkan rakyat, tetapi tidak selalu membagikannya secara transparan.
Penyebab asimetri informasi antara pemerintah dan rakyat, antara lain, kurangnya transparansi pemerintah. Pemerintah sering kali tidak mengungkapkan informasi secara terbuka, baik karena alasan politik, keamanan, atau ketidakmampuan dalam menyampaikan informasi. Kedua, kesenjangan pendidikan dan literasi. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang cukup terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait ekonomi, hukum, dan keuangan negara.
Ketiga, birokrasi yang rumit. Informasi yang dimiliki pemerintah sering kali tersembunyi dalam dokumen resmi yang sulit diakses atau dipahami oleh masyarakat umum. Lalu, pengaruh media dan hoaks. Media memiliki peran dalam menyebarkan informasi, tetapi terkadang informasi yang beredar tidak objektif atau dipolitisasi. Hoaks juga memperburuk kesenjangan informasi antara pemerintah dan rakyat.
Kurangnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan juga menjadi penyebab. Jika rakyat tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, mereka cenderung tidak memahami keputusan yang dibuat oleh pemerintah.
Dampak asimetri informasi itu masyarakat bisa tidak percaya terhadap pemerintah. Jika rakyat merasa pemerintah tidak transparan, kepercayaan publik menurun, yang bisa berujung pada ketidakstabilan politik. Selain itu, membuat kebijakan berjalan tidak efektif. Jika pemerintah tidak memahami kebutuhan rakyat karena kurangnya komunikasi dua arah, kebijakan yang diambil bisa tidak tepat sasaran. Kemudian, meningkatnya potensi korupsi. Ketika informasi tidak terbuka, peluang untuk praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang semakin besar.
Dalam konteks di lembaga publik Pertamina, kondisi demikian dimanfaatkan oknum pejabat dan pelaku korupsi untuk menyembunyikan praktik ilegal. Misalnya, mark-up proyek. Informasi teknis dan anggaran proyek sengaja dikaburkan untuk menggelembungkan biaya. Lalu, manipulasi laporan keuangan. Data keuangan tidak diungkapkan secara utuh, menghambat pengawasan eksternal. Alokasi dana subsidi tidak transparan, memicu kebocoran ke pihak yang tidak bertanggung jawab.
Akibatnya, celah informasi tersebut memfasilitasi korupsi besar-besaran yang sulit dideteksi hingga menimbulkan kerugian triliunan rupiah. Masyarakat dan pemerintah sebagai pemilik saham seringkali terlambat menyadari.
Antisipasi Asimetri Informasi
Sebetulnya, sebagai salah satu antisipasi, sudah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini sejatinya hadir sebagai respons terhadap budaya kerahasiaan di sektor publik. UU KIP mewajibkan badan publik, termasuk BUMN seperti Pertamina, untuk membuka akses informasi secara proaktif dan responsif.
Beberapa poin kaitannya dengan pencegahan korupsi, pertama transparansi anggaran dan proyek. Badan public wajib mempublikasikan dokumen anggaran, tender, dan laporan keuangan, sehingga meminimalkan ruang untuk mark-up atau manipulasi. Kedua, makanisme pengaduan publik. Masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi terkait kebijakan badan publik bersangkutan sehingga dapat memaksa akuntabilitas. Badan publik yang menolak memberikan informasi publik pun dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.
Jika UU ini diimplementasikan secara optimal, asimetri informasi dapat dikikis karena seluruh proses pengambilan keputusan dan penggunaan dana negara terbuka untuk diawasi. Namun, meski UU 14/2008 menjadi senjata hukum untuk melawan asimetri informasi, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya, resistensi kultural. Budaya tertutup di tubuh badan publik seringkali menganggap informasi strategis sebagai “rahasia perusahaan” atau dapur internal. Padahal, jelas anggaran mereka berasal dari publik.
Karena itu, pekerjaan besar kita semua adalah memaksimalkan UU 14/2008. Mengarusutamakan UU tersebut dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, UU KIP berjalan efektif mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Diperlukan gerakan-gerakan terstruktur, sistematis, dan masif. Pertama, digitalisasi informasi publik. Membangun platform-platform terbuka yang memuat real-time data keuangan, proyek, pengadaan barang dan jasa, hingga kinerja badan publik. Kedua, edukasi publik. Makin masif melaksanakan diseminiasi tentang hak masyarakat mengakses informasi dan mekanisme pengaduan.
Ketiga, sinergisitas dengan dengan Lembaga penegak hukum seperti KPK. Integrasi UU KIP dengan UU Tipikor untuk memperkuat sanksi dan investigasi korupsi. Selain itu, dilakukan audit berkala. Baik dari internal atapun bahkan lembaga internasional untuk memastikan kepatuhan transparansi.
Skandal korupsi Pertamina dan di beberapa badan publik lain, mencerminkan bahaya asimetri informasi yang dibiarkan berkembang di institusi-insttusi strategis. UU 14/2008 bukan hanya dapat menjadi solusi hukum, melainkan juga alat demokratisasi informasi untuk memutus mata rantai korupsi.
Namun, tentu saja efektivitasnya bergantung pada komitmen pemerintah, keseriusan penegakan hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal transparansi. Dengan demikian, kejadian serupa dapat dicegah, dan kepercayaan publik dapat dipulihkan. (*)