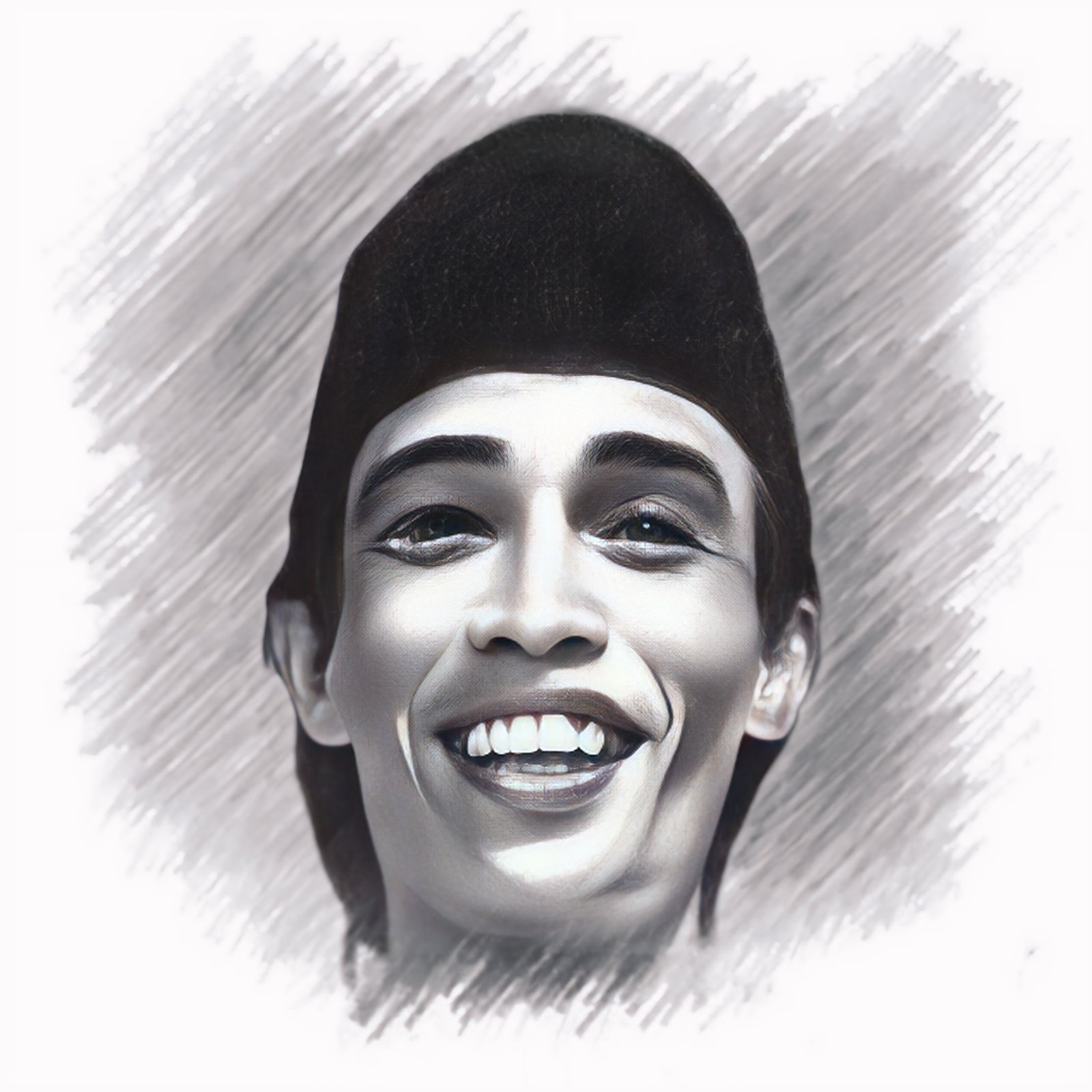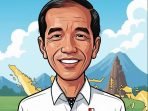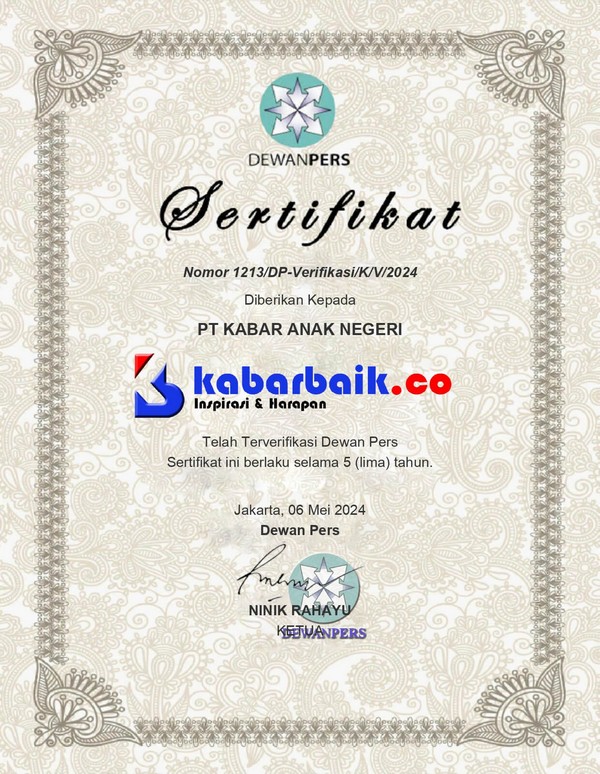OLEH: M. SHOLAHUDDIN*)
SAYA sengaja datang ke Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya. Di malam pertama Ramadan 1446 H. Menonton Persebaya melawan Persib Bandung. Jauh-jauh waktu sudah diagendakan. Bagi saya, pertandingan ini bukan sebatas menang atau kalah. Lebih dari itu. Saya tinggal memutar niat. ’’Tadarus’’ di stadion. Menguatkan ilmu tentang arti hidup dan kehidupan.
Dari rumah, saya memilih naik motor. Selepas berbuka puasa, ditemani seorang kawan, langsung meluncur ke Stadion GBT. Bersyukur hari tidak hujan. Membelah jalan. Tidak sampai 30 menit sudah tiba. Seorang kawan asal Bangkalan sudah menunggu. Ribuan orang pun sudah mulai merangsek. Memadati stadion di wilayah Benowo, Surabaya, itu. Suasana demikian sungguh menjadi kelangenan tersendiri.
Sepak bola bukan sekadar olahraga. Ia juga sebuah fenomena budaya. Menyatukan jutaan orang dari berbagai latar belakang. Namun, ada beda mendasar antara menonton di layar kaca dengan menyaksikan langsung di stadion. Bagi sebagian orang, termasuk saya, datang ke stadion adalah ritual sakral. Menghubungkan esensi manusia sebagai seorang makhluk. Kebersamaan, emosi mentah, dan kehadiran yang otentik.
Di era digital, di mana hampir semua hal bisa diakses secara virtual, kehadiran fisik di stadion seolah menjadi simbol perlawanan terhadap dunia yang semakin terabstraksi. Saat duduk di tribun, Anda merasakan angin, mencium beragam aroma, mendengar gemuruh dentuman, hingga guratan ribuan ekspresi wajah-wajah suporter yang tak tertangkap kamera. Tentu, menjadi pengalaman tangible yang tak bisa direplikasi oleh layar atau komentar penyiar.
Teringat, seorang filsuf Martin Heidegger yang pernah membahas tentang konsep Dasein atau keberadaan-ada. Di mana manusia menemukan makna melalui kehadiran langsung di dunia. Di stadion, Anda menjadi bagian dari momen yang nyata. Bukan sekadar penonton beku yang minim ekspresi.
Stadion adalah ruang kosong. Di mana Anda akan melebur menjadi satu entitas. Sebagai seorang suporter. Sorakan, nyanyian, dan bahkan kutukan bersama menciptakan gelombang energi yang menggetarkan. Emile Durkheim, sosiolog Prancis, menyebut fenomena ini sebagai collective effervescence. Di sinilah terjadi emosi kolektif mencapai puncak dan menghasilkan rasa persatuan magis. Saat gol tercipta, sorak dan tos dengan orang di sebelah yang Anda tak kenal sekalipun, bukan lagi hal aneh. Di sini, batas sosial, ekonomi, atau politik runtuh. Semua bersatu dalam satu identitas.
Datang ke stadion adalah ritual yang penuh dengan makna dan simbol. Dari memakai jersey tim, menyanyikan lagu, hingga tradisi unik lainnya. Ritual-ritual ini bukan hanya hiburan, melainkan cara menegaskan identitas dan keberlanjutan sejarah. Stadion menjadi tempat ingatan yang menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan.
Menonton sepak bola di stadion juga sebetulnya mengajarkan tentang penerimaan akan ketidakpastian. Tidak ada tombol pause atau replay saat Anda berada di tribun. Setiap detik adalah momen yang unik dan tak terulang. Tendangan yang meleset, tabrakan keras, keputusan wasit yang terkadang kontroversial, atau hujan tiba-tiba yang mengubah alur permainan.
Filsuf Stoic seperti Seneca mungkin akan melihat ini sebagai metafora kehidupan. Sebagai makhluk, kita tak bisa mengontrol segalanya. Namun, bisa memilih bagaimana merespons. Di stadion, kita belajar untuk merayakan kemenangan dengan rendah hati dan menerima kekalahan dengan lapang dada. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang susah, terkadang bahagia.
Di tengah dominasi media sosial dan streaming, stadion adalah sebuah ruang analog. Mengembalikan kemanusiaan kita. Tidak ada algoritma yang mengatur apa yang Anda lihat, tidak ada spoiler dari notifikasi ponsel. Kita hanya fokus pada pertandingan, terlibat sepenuhnya dengan indra dan emosi. Jean Baudrillard, filsuf postmodern, mungkin menyebut stadion sebagai ruang hiperrealitas, yang justru lebih “nyata” daripada realitas virtual yang kita hidupi sehari-hari.
Karena itu, menonton sepak bola langsung di stadion bukanlah sekadar hobi. Tapi, ekspresi filosofis tentang cara kita menjalani hidup. Ia mengingatkan bahwa manusia adalah makna sosial yang membutuhkan kebersamaan, makhluk emosional yang merindukan keaslian, dan pencari makna yang menemukan identitas melalui ritual.
Di tengah gemuruh lautan suporter, kita dapat menemukan bagian dari diri yang seringkali terlupakan: Hasrat untuk hidup sepenuhnya, di sini dan kini. Seperti sebuah pepatah Italia: Il calcio è la più importante delle cose meno important (Sepak bola adalah hal paling penting di antara hal-hal yang tidak penting).
Di stadion, kita memahami paradoks dengan seluruh jiwa. Bagaimana mungkin terjadi orang yang sudah digaji negara sebesar Rp 2 miliar setiap bulan, masih menggarong uang Rp 193,7 triliun? Memikirkan itu sungguh membuat mules. Yang penting, malam itu Persebaya Surabaya menang 4-1 atas Persib Bandung. Tapi, kalau memang tidak suka bola, jangan dipaksa-paksa. Lakum dinukum, waliyadin Wallahu A’lam. (*)
—-
*) M. SHOLAHUDDIN, penulis tinggal di Kabupaten Gresik