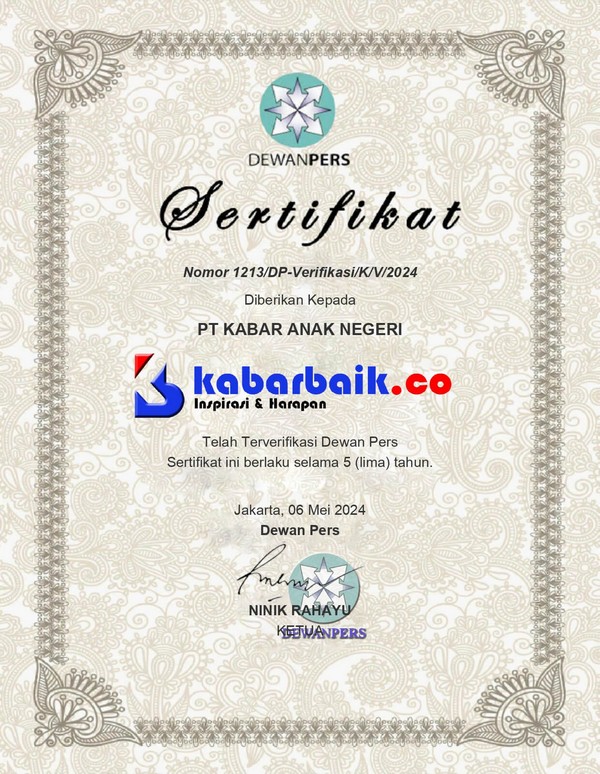KabarBaik,co- Kediri, sebuah daerah di Jawa Timur, tidak bisa dilepaskan dari aroma sedap tembakau. Dari sinilah lahir PT Gudang Garam, sebuah nama yang menjadi ikon industri kretek Indonesia.
Semua bermula pada 1958 silam. Saat Surya Wonowidjojo atau Tjoa Ing Hwie, memutuskan mendirikan pabrik rokok sendiri, setelah keluar dari usaha milik pamannya. Dengan berbekal tekad, loyalitas 50 pekerja, dan modal keberanian, Surya menapaki jalan panjang yang kelak menjadikan Gudang Garam sebagai salah satu produsen rokok terbesar di negeri ini.
Perjalanan perusahaan kemudian diteruskan anak-anaknya. Kini, tongkat estafet berada di tangan Susilo Wonowidjojo, generasi kedua keluarga. Melalui PT Suryaduta Investama, keluarga Wonowidjojo mengendalikan hampir 70 persen saham Gudang Garam.
Di bawah kepemimpinan Susilo, nama keluarga ini sempat mengilap dalam daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes. Pada 2018, total kekayaan mereka dilaporkan mencapai lebih dari 9 miliar dolar AS. Namun, seiring dengan kinerja perusahaan yang menurun, harta itu perlahan menyusut, hingga kini hanya sekitar 2,9 miliar dolar (sekitar Rp 43 triliun).
Prestisius Membangun Bandara Dhoho
Keberhasilan Gudang Garam bukan hanya terlihat dari pabrik rokok yang menjulang di Kediri. Perusahaan ini juga meninggalkan jejak lain yang jauh melampaui dunia tembakau. Yakni, pembangunan Bandara Internasional Dhoho. Bandara ini unik. Sebab, menjadi proyek pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai sektor swasta, tanpa dana pemerintah. Melalui anak usaha PT Surya Dhoho Investama, Gudang Garam menghadirkan sebuah infrastruktur modern yang diharapkan mempercepat konektivitas Kediri dan sekitarnya.
Bandara ini resmi melakukan penerbangan perdana pada April 2024 lalu. Armada Citilink menghubungkan Kediri–Jakarta. Enam bulan kemudian, pada Oktober, Dhoho diresmikan dengan penuh kebanggaan oleh jajaran menteri. Namun, sayangnya euforia itu tak berlangsung lama. Sejak pertengahan 2025, penerbangan berhenti sementara karena masalah armada maskapai.
Sejatinya, pada Agustus 2025, Bandara Dhoho tersebut dinaikkan statusnya menjadi internasional. Namun, aktivitas penerbangan belum juga bergulir. Sebuah simbol besar berdiri megah, tetapi masih menunggu peran nyata.
Di balik megaproyek prestisius tersebut, kinerja inti Gudang Garam justru tercatat meredup. Pada 2024, laba bersih anjlok lebih dari 80 persen, dari Rp 5,3 triliun menjadi tak sampai Rp 1 triliun. Semester pertama 2025 kondisinya tercatat makin tertekan. Laba bersih hanya Rp 117 miliar, turun 87 persen dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan yang dulu sempat tembus Rp 118 triliun, kini susut lebih dari Rp 20 triliun.
Biangnya disebut beragam. Mulai cukai yang semakin mencekik, persaingan pasar rokok yang ketat, hingga permintaan yang menurun, baik di dalam negeri maupun ekspor. Margin keuntungan tergerus. Pasar rokok elektrik yang tengah tumbuh, tak banyak digarap karena regulasi yang menyamakannya dengan rokok konvensional. Situasi ini menimbulkan dampak nyata: isu pemutusan hubungan kerja di sejumlah pabrik mulai menyeruak, membuat ribuan pekerja cemas.
Nasib Gudang Garam kini berada di persimpangan. Di satu sisi, membangun kejayaan dari gulungan kretek yang menemani hidup banyak orang Indonesia. Di sisi lain, mereka mencoba meninggalkan jejak baru dengan menghadirkan bandara megah di Kediri. Namun, saat asap keuntungan semakin tipis, bandara yang dibangun justru berdiri sepi.
Pertanyaannya, mampukah Gudang Garam menghidupkan kembali api kejayaannya? Ataukah cerita ini akan berakhir sebagai simbol kebesaran yang perlahan memasuki masa senja?
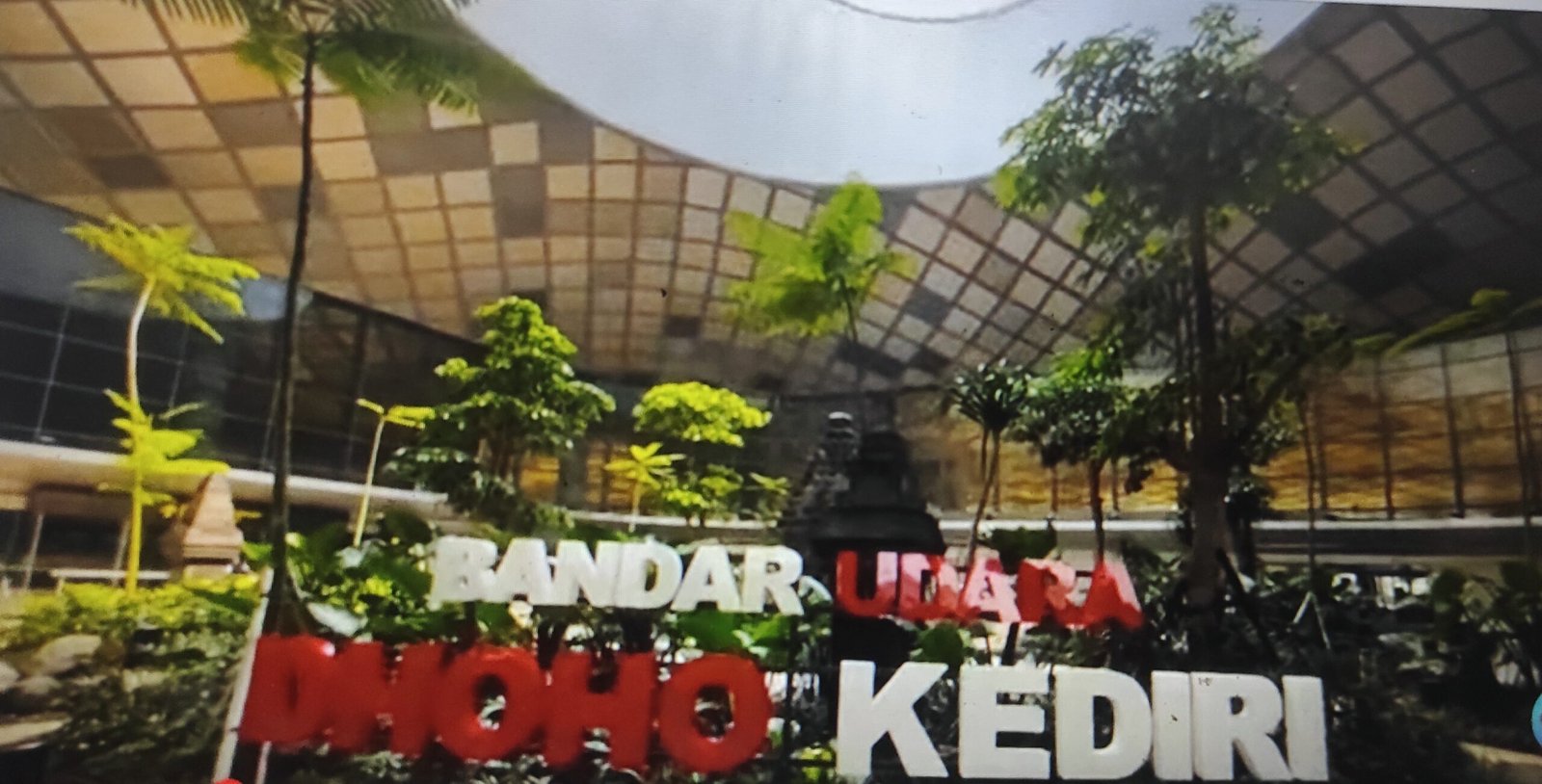
Bayang-Bayang Sawah yang Terdiam
Di dalam lorong pabrik yang dulu riuh oleh ritmis lintingan kretek, kini muncul bayang-bayang yang semakin terasa. Penurunan tajam laba Gudang Garam, telah menjadi alarm sosial, bukan sekadar angka dalam laporan keuangan.
Buruh-buruh yang dulu menjadi denyut pabrik, kini jelas tak seperti dulu. Pekerja yang mencapai puluhan ribu di Kediri itu, tentu merasakan getar kekhawatiran, walaupun sejauh ini belum ada kabar pasti data PHK kategori massal.
Di sudut desa petani tembakau, asap harapan ikut memudar. Harga tembakau jenis kasturi, belakangan ikut tertekan. Dulu, komoditas tembakau ini dihargai Rp 47 ribu per kilogram. Kini, dilaporkan merosot ke kisaran Rp 33 ribu. Kondisi ini yang membuat para petani merugi jutaan rupiah per lokasi. Tekanan yang tak hanya finansial, melainkan juga emosional,
Dengan Gudang Garam sebagai salah satu pembeli utama, momentum penurunan laba sementara bakal menciptakan efek domino. Panen yang terancam gagal terjual optimal, kredit musiman berpotensi menumpuk, dan petani serta buruh tembakau tercengkeram antara harapan dan realitas yang kian suram.
Kediri, yang bertahun-tahun tumbuh subur dari industri rokok, tentu turut terdampak. Berdasarkan data, Gudang Garam menyumbang sekitar 70 persen dari PDRB Kota Kediri, dengan penyerapan tenaga kerja langsung mencapai sekitar 25.600 jiwa. Bahkan, bisa sampai 20 persen jika termasuk tenaga sektor distribusi dan UMKM penunjang.
Kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) jelas, sebagian pendapatan daerah bergantung pada cukai hasil tembakau dan investasi perusahaan. Kini, kursi pendapatan daerah bisa jadi bergetar. Data BPS menyebut 80 persen ekonomi Kediri, bergantung pada industri kretek.
Konsekuensinya, PAD Kediri terancam stagnan, bahkan menurun. Keterbatasan dana fiskal berpeluang menghantam layanan publik, sekolah, kesehatan, hingga pembangunan sarana, yang selama ini mendapat andil kontribusi cukai dan program CSR Gudang Garam.
Di tengah gemerlap megaproyek infrastruktur, Bandara Dhoho, tol, taman kota, tampaknya pembangunan fisik berjalan di atas fondasi ekonomi yang terbilang kini rentan. Bandara megah bisa berdiri, tetapi jika ekonomi utamanya tertekan, manfaat multiplikasi terhadap pariwisata dan perdagangan akan sulit merekah. Pertumbuhan kota bisa terlihat, tapi tak banyak terasa bagi masyarakatnya.
Menyulam Harapan Jalan ke Depan
Di tengah kabut tersebut, arah jalan keluar butuh sinergisitas dan kolaborasi. Antara perusahaan, petani, buruh, dan pemerintah. Pertama, perlu dorongan bagi diversifikasi ekonomi. Sejumlah pakar menyarankan, pengembangan sektor kreatif, UMKM, pariwisata budaya, dan peningkatan SDM agar menghadirkan sumber pendapatan alternatif dan mengurangi ketergantungan struktural pada industri rokok.
Kedua, petani tembakau butuh dukungan kokoh. Mulai regulasi harga minimal, skema kredit mikro berbunga rendah, dan kerjasama langsung antara koperasi petani dan pabrik untuk stabilitas harga. Hal ini vital karena bukan hanya soal pertanian, melainkan soal rasa aman dan kelanjutan denyut pedesaan.
Ketiga, untuk buruh pabrik, perlindungan sosial dan pelatihan ulang atau reskilling sangat penting. Jika permintaan rokok terus melemah, tenaga kerja dapat diarahkan ke sektor konstruksi seperti bandara, tol, logistik, atau jasa pendukung wisata yang tumbuh di kawasan itu.
Keempat, pemerintah perlu mengoptimalkan dana bagi hasil cukai sebagai jaring pengaman sosial. Misalnya, dengan memberikan alokasi khusus untuk modal kerja UMKM, bantuan langsung buruh harian, dan subsidi pendidikan anak buruh.
Yang jelas, dari asap kretek hingga dermaga bandara, cerita Kediri berkisah tentang mimpi yang tinggi, tetapi juga ketergantungan yang berat. Ketika gudang meredup dan keuntungan pudar, tentu masyarakat turut merasakan dentuman yang dalam. Tak hanya di pabrik, tetapi juga di sawah-sawah, di sekolah, dan di rumah-rumah sederhana.
Tugas bersama kini bukan sekadar memperbaiki angka laba, melainkan juga memperkuat ekonomi lokal dari dalam. Membangun ketahanan bukan hanya dari peluang, tetapi dari ikatan sinergisitas dan kolaborasi elemen atau pilar-pilar terkait. Buruh, petani, dan pemerintah. (*)