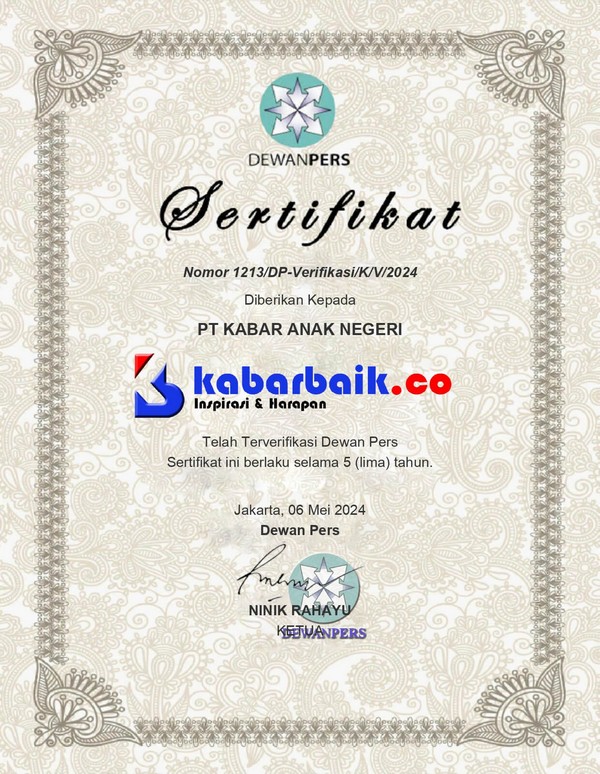OLEH: IMMANUEL YOSUA*)
Tanggal 28 September telah berlalu, namun gaungnya sebagai Hari Hak untuk Tahu Internasional masih samar terdengar. Ini adalah hari yang sederhana, tetapi fundamental. Hari untuk mengingatkan setiap warga negara: kita memiliki hak untuk tahu. Ini bukan anugerah atau hak istimewa, melainkan hak dasar yang melekat pada setiap individu dalam negara demokrasi.
Namun, realitas di Indonesia kerap terasa ironis. “Hak untuk tahu” seringkali diperlakukan seperti hadiah yang harus dinanti. Untuk mendapatkan informasi saja, kita harus melewati birokrasi yang berbelit, menunggu lama, dan dalam banyak kasus, informasi itu malah ditutup-tutupi. Ini menunjukkan adanya resistensi budaya transparansi dalam tubuh birokrasi kita.
Beruntung, di Jawa Timur, Komisi Informasi (KI Jatim) menunjukkan komitmen yang berbeda. Sejak 28 September hingga hari ini, mesin sosialisasi mereka terus bergerak. Mereka berkeliling, menyentuh kabupaten, kota, kampus, hingga pelosok desa. Aktivitas ini bukan sekadar show of force atau upaya formalitas menggugurkan kewajiban.
Mereka secara aktif mengajak pemerintah untuk berani terbuka, dan masyarakat untuk sungguh-sungguh memahami hak-haknya. Tujuannya tunggal: menyadarkan semua pihak bahwa keterbukaan bukanlah ancaman bagi kekuasaan, melainkan indikasi dari tata kelola pemerintahan yang sehat dan matang.
Kegiatan KI Jatim sangat beragam dan menyentuh akar masalah: diskusi publik, pelatihan, pendampingan, hingga ajudikasi sengketa data. Di mana pun mereka berada, pesannya selalu bergema kuat: “Informasi adalah milik rakyat. Jangan disembunyikan.” Dalam era digital saat ini, keterbukaan telah menjadi kebutuhan mendasar, bukan lagi pilihan.
Namun, upaya membumikan keterbukaan ini tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada KI Jatim. Mereka hanyalah salah satu pintu. Jika pintu dibuka lebar tetapi “rumah birokrasi” masih gelap dan kotor, siapa yang akan merasa nyaman masuk?
Oleh karena itu, ini adalah gerakan kolektif. Media harus berani terus mengawal kebijakan publik, bukan hanya puas menulis rilis resmi. Organisasi non-pemerintah (NGO) wajib membantu meningkatkan literasi warga—agar mampu membedakan mana data yang faktual dan mana sekadar opini atau hoaks. Yang tak kalah krusial, pejabat publik dan tokoh masyarakat harus menjadi teladan transparans. Sebab, kepemimpinan yang tulus selalu lebih meyakinkan melalui contoh nyata daripada sekadar retorika.
Jika semua elemen bangsa bergerak, keterbukaan tidak akan lagi menjadi sekadar proyek pemerintah. Ia akan menjelma menjadi gerakan rakyat semesta yang mengakar kuat.
Masalahnya terletak pada budaya. Kita belum terbiasa dengan “terang”. Masih banyak pejabat yang nyaman bersembunyi di balik tirai birokrasi. Mereka berdalih, “Kalau semua dibuka, nanti malah merepotkan.”
Padahal, faktanya justru sebaliknya. Keterbukaan memudahkan pengawasan, menekan potensi korupsi, dan meningkatkan efisiensi. Keterbukaan tidak mahal. Ia hanya membutuhkan niat tulus dan keberanian moral.
Kepala desa cukup transparan memasang laporan realisasi dana desa di papan pengumuman desa. Sekolah cukup detail menjelaskan penggunaan dana BOS kepada wali murid. Lembaga keagamaan harus jujur soal pengelolaan sumbangan umat. Sederhana, namun seringkali hal yang sederhana justru yang paling berat diwujudkan.
Rasa takut, keraguan, dan ketidakbiasaan untuk transparan menjadi benteng yang harus dirobohkan. Di sinilah letak pentingnya peran KI Jatim. Mereka bukan hanya lembaga penegak, tetapi penyala lilin harapan. Mereka mendampingi badan publik, memberikan edukasi, dan mendengarkan keluhan rakyat. Perlahan, resistensi itu mulai luntur, dan lembaga-lembaga yang tadinya tertutup mulai berani membuka diri.
Di tengah derasnya arus disinformasi dan hoaks di era digital, keterbukaan adalah udara segar yang menenangkan. Ia menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dan perlu kita ingat, sebuah bangsa hanya bisa berdiri tegak dan berkelanjutan di atas fondasi yang tunggal: kepercayaan rakyat.
Namun, keterbukaan juga menuntut kedewasaan dari semua pihak. Pemerintah harus siap dikritik tanpa perlu marah dan defensif. Rakyat harus berani bertanya dengan etika, bukan mencaci. Media wajib teliti dan akurat, tidak sensasional. Sementara NGO harus jujur dalam advokasi, tidak menunggangi isu atau memanfaatkan kesalahan untuk kepentingan pragmatis.
Mengapa demikian? Karena keterbukaan informasi publik ibarat pisau tajam bermata dua. Jika digunakan dengan tepat dan didasari niat baik, ia akan melahirkan tata kelola yang baik dan demokrasi yang kuat. Namun, jika disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, atau memanipulasi fakta, yang lahir bukanlah kemajuan—melainkan kekacauan sosial dan delegitimasi.
Oleh karena itu, saatnya kita memulai perjalanan memaknai keterbukaan informasi publik dari lingkup terkecil: dari kantor, dari komunitas, bahkan dari rumah. Buka ruang bicara. Terima perbedaan pendapat. Tunjukkan laporan. Semua ini bukan untuk pamer kekuatan, melainkan sebagai bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab moral.
Saya memiliki keyakinan, jika keterbukaan sudah benar-benar menjadi budaya, kita tidak perlu lagi secara khusus memperingati Hari Hak untuk Tahu. Sebab, informasi sudah mengalir secara alamiah. Pemerintah pun tak perlu lagi merasa takut, karena mereka sudah meraih kembali kepercayaan rakyat.
Itulah hari ketika keterbukaan benar-benar membumi. Bukan sekadar teks dalam undang-undang, tetapi menjadi cara hidup berbangsa dan bernegara.
Keterbukaan informasi publik adalah tanggung jawab semua. (*)
* Penulis adalah Koordinator Umum Perkumpulan Mitra Publik Indonesia (MPI) dan pemerhati keterbukaan informasi publik, mantan Ketua KPID Jatim